Health System Resilience & Global Governance
Sesi ini dipandu oleh Shita Listyadewi, S.IP., MM, MPP, peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK UGM). Shita membuka sesi dengan menjelaskan sistem kesehatan menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tekanan jangka pendek (seperti penyakit musiman), hingga tekanan jangka panjang (seperti perubahan iklim). Dengan demikian, berbagai pilar sistem kesehatan perlu diperkuat untuk membangun sistem yang resilien.
 Pembicara pertama pada sesi plenary ketiga ini adalah Dr. Somil Nagpal yang merupakan Senior (Lead) Health Specialist di The World Bank. Paparan Somil mengambil tajuk “Financing Resilient Health Systems in the Face of Global Crises”. Dalam paparannya, Somil, melalui studi kasus kawasan Asia Pasifik Timur (East Asia Pacific/ EAP), menggarisbawahi bahwa tantangan keberlanjutan pendanaan sistem kesehatan dapat mempengaruhi pencapaian sistem kesehatan dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC). Kondisi finansial berbagai negara pasca pandemi COVID-19 beragam. Sebagian negara, seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan Filipina, mampu mencapai kondisi keuangan yang melampaui kondisi pra pandemi, namun beberapa negara lain, misalnya Palau dan Vanuatu, mengalami penurunan Gross Domestic Product (GDP) per kapita, bahkan mencapai dibawah kondisi pra pandemi 2019. Somil juga menggambarkan capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan UHC, di mana kawasan Pasifik menempati peringkat kedua terendah dibandingkan kawasan lain dalam tahun-tahun terakhir. Dengan demikian, jalan menuju UHC masih terlihat panjang sekaligus berliku dengan adanya kesulitan-kesulitan finansial yang dialami berbagai negara. Somil menutup presentasinya dengan menekankan bahwa repriotisasi adalah kunci untuk mendukung keberlanjutan pendanaan kesehatan di tengah berbagai krisis. read more
Pembicara pertama pada sesi plenary ketiga ini adalah Dr. Somil Nagpal yang merupakan Senior (Lead) Health Specialist di The World Bank. Paparan Somil mengambil tajuk “Financing Resilient Health Systems in the Face of Global Crises”. Dalam paparannya, Somil, melalui studi kasus kawasan Asia Pasifik Timur (East Asia Pacific/ EAP), menggarisbawahi bahwa tantangan keberlanjutan pendanaan sistem kesehatan dapat mempengaruhi pencapaian sistem kesehatan dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC). Kondisi finansial berbagai negara pasca pandemi COVID-19 beragam. Sebagian negara, seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan Filipina, mampu mencapai kondisi keuangan yang melampaui kondisi pra pandemi, namun beberapa negara lain, misalnya Palau dan Vanuatu, mengalami penurunan Gross Domestic Product (GDP) per kapita, bahkan mencapai dibawah kondisi pra pandemi 2019. Somil juga menggambarkan capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan UHC, di mana kawasan Pasifik menempati peringkat kedua terendah dibandingkan kawasan lain dalam tahun-tahun terakhir. Dengan demikian, jalan menuju UHC masih terlihat panjang sekaligus berliku dengan adanya kesulitan-kesulitan finansial yang dialami berbagai negara. Somil menutup presentasinya dengan menekankan bahwa repriotisasi adalah kunci untuk mendukung keberlanjutan pendanaan kesehatan di tengah berbagai krisis. read more





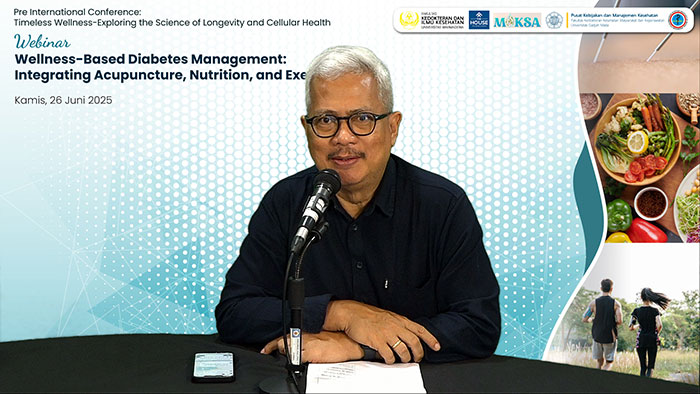
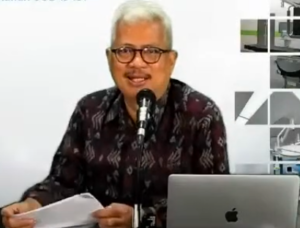
 Sesi talkshow dimulai dengan pembahasan terkait dengan bagaimana kaitan antara policy dan science serta peran masing-masing untuk keberlanjutan sistem kesehatan di negara berkembang, terutama di Indonesia, Thailand, dan Malaysia.
Sesi talkshow dimulai dengan pembahasan terkait dengan bagaimana kaitan antara policy dan science serta peran masing-masing untuk keberlanjutan sistem kesehatan di negara berkembang, terutama di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Pembicara pertama pada sesi plenary ketiga ini adalah Dr. Somil Nagpal yang merupakan Senior (Lead) Health Specialist di The World Bank. Paparan Somil mengambil tajuk “Financing Resilient Health Systems in the Face of Global Crises”. Dalam paparannya, Somil, melalui studi kasus kawasan Asia Pasifik Timur (East Asia Pacific/ EAP), menggarisbawahi bahwa tantangan keberlanjutan pendanaan sistem kesehatan dapat mempengaruhi pencapaian sistem kesehatan dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC). Kondisi finansial berbagai negara pasca pandemi COVID-19 beragam. Sebagian negara, seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan Filipina, mampu mencapai kondisi keuangan yang melampaui kondisi pra pandemi, namun beberapa negara lain, misalnya Palau dan Vanuatu, mengalami penurunan Gross Domestic Product (GDP) per kapita, bahkan mencapai dibawah kondisi pra pandemi 2019. Somil juga menggambarkan capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan UHC, di mana kawasan Pasifik menempati peringkat kedua terendah dibandingkan kawasan lain dalam tahun-tahun terakhir. Dengan demikian, jalan menuju UHC masih terlihat panjang sekaligus berliku dengan adanya kesulitan-kesulitan finansial yang dialami berbagai negara. Somil menutup presentasinya dengan menekankan bahwa repriotisasi adalah kunci untuk mendukung keberlanjutan pendanaan kesehatan di tengah berbagai krisis.
Pembicara pertama pada sesi plenary ketiga ini adalah Dr. Somil Nagpal yang merupakan Senior (Lead) Health Specialist di The World Bank. Paparan Somil mengambil tajuk “Financing Resilient Health Systems in the Face of Global Crises”. Dalam paparannya, Somil, melalui studi kasus kawasan Asia Pasifik Timur (East Asia Pacific/ EAP), menggarisbawahi bahwa tantangan keberlanjutan pendanaan sistem kesehatan dapat mempengaruhi pencapaian sistem kesehatan dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC). Kondisi finansial berbagai negara pasca pandemi COVID-19 beragam. Sebagian negara, seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan Filipina, mampu mencapai kondisi keuangan yang melampaui kondisi pra pandemi, namun beberapa negara lain, misalnya Palau dan Vanuatu, mengalami penurunan Gross Domestic Product (GDP) per kapita, bahkan mencapai dibawah kondisi pra pandemi 2019. Somil juga menggambarkan capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan UHC, di mana kawasan Pasifik menempati peringkat kedua terendah dibandingkan kawasan lain dalam tahun-tahun terakhir. Dengan demikian, jalan menuju UHC masih terlihat panjang sekaligus berliku dengan adanya kesulitan-kesulitan finansial yang dialami berbagai negara. Somil menutup presentasinya dengan menekankan bahwa repriotisasi adalah kunci untuk mendukung keberlanjutan pendanaan kesehatan di tengah berbagai krisis. Pembicara pertama adalah Dr. Maarten Kok yang membahas tentang “Can AI Help Us Decide? Are More Expensive Medicines Worth It”. Dalam presentasi ini, Dr Maarten menceritakan beberapa studinya di Indonesia. Salah satunya menjelaskan tentang sejarah dari pelaksanaan universal health coverage di Indonesia yang menghasilkan jaminan kesehatan nasional sebagai aset politik presiden. Kemudian, stud
Pembicara pertama adalah Dr. Maarten Kok yang membahas tentang “Can AI Help Us Decide? Are More Expensive Medicines Worth It”. Dalam presentasi ini, Dr Maarten menceritakan beberapa studinya di Indonesia. Salah satunya menjelaskan tentang sejarah dari pelaksanaan universal health coverage di Indonesia yang menghasilkan jaminan kesehatan nasional sebagai aset politik presiden. Kemudian, stud