
Innovations and Solutions for Sustainable Health Systems
Pada sesi ini terdapat 5 pembicara yang dimoderatori oleh Andreasta Meliala, Dr. dr. DPH., MKes, MAS.
Materi sesi pertama disampaikan oleh Kristin Darundiyah, S.Si, MSc. PH selaku Ketua Tim kerja Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Indonesia. Kristin mengangkat topik “The Ministry of Health’s Strategy for Advancing Environmentally Friendly Healthcare Services” sebagai bentuk strategi Kementerian Kesehatan untuk memajukan pelayanan kesehatan yang ramah lingkungan. Kristin menjelaskan AMR dan perubahan iklim telah menjadi ancaman global akhir-akhir ini. Ketika digabungkan, keduanya memperburuk kerentanan dan mempercepat penyebaran penyakit. Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan dalam peraturan dan strategi nasional 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui pengendalian penggunaan antibiotik secara intensif dan beberapa inovasi untuk kesehatan lingkungan, seperti penggunaan WASH FIT, ME-SMILE, dan inisiatif lain yang menggunakan teknologi dan alat AI. Lebih lanjut, Kristin menggarisbawahi perlunya kolaborasi multisektor untuk mendorong upaya pengendalian AMR dan kesehatan lingkungan, serta strategi terpadu untuk meningkatkan sanitasi dan penggunaan kerangka hukum di seluruh Indonesia.
 Sesi kedua dibawakan oleh Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid, selaku Professor Kebijakan & Ekonomi Kesehatan, di UKM & IMU, Malaysia. Aljunid mengangkat topik “Health Financing for Universal Health Coverage: Current and Future Challenges” untuk menampilkan kondisi terkini dan tantangan masa depan keuangan kesehatan untuk UHC. Aljunid menjelaskan bahwa UHC memastikan semua orang memiliki akses ke pelayanan kesehatan esensial tanpa kesulitan keuangan. Hal ini penting untuk mendorong pemerataan kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan populasi. Namun, untuk mencapai UHC, ada banyak perselisihan dan tantangan yang harus diatasi. Kapasitas fiskal yang terbatas, biaya out-of-pocket yang tinggi, dan mekanisme pendanaan yang terfragmentasi adalah beberapa tantangan, terutama dalam pembiayaan kesehatan untuk UHC. Di sisi lain, tantangan yang muncul, seperti meningkatnya PTM, populasi yang menua, pandemi, dan krisis, dapat membalikkan keadilan kesehatan dan memperdalam kesenjangan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus lebih menaruh perhatian pada UHC yang harus dicapai dengan keuangan yang bijaksana. Aljunid menutup dengan pernyataan bahwa pendekatan strategis dan inisiatif inovatif harus diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.
Sesi kedua dibawakan oleh Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid, selaku Professor Kebijakan & Ekonomi Kesehatan, di UKM & IMU, Malaysia. Aljunid mengangkat topik “Health Financing for Universal Health Coverage: Current and Future Challenges” untuk menampilkan kondisi terkini dan tantangan masa depan keuangan kesehatan untuk UHC. Aljunid menjelaskan bahwa UHC memastikan semua orang memiliki akses ke pelayanan kesehatan esensial tanpa kesulitan keuangan. Hal ini penting untuk mendorong pemerataan kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan populasi. Namun, untuk mencapai UHC, ada banyak perselisihan dan tantangan yang harus diatasi. Kapasitas fiskal yang terbatas, biaya out-of-pocket yang tinggi, dan mekanisme pendanaan yang terfragmentasi adalah beberapa tantangan, terutama dalam pembiayaan kesehatan untuk UHC. Di sisi lain, tantangan yang muncul, seperti meningkatnya PTM, populasi yang menua, pandemi, dan krisis, dapat membalikkan keadilan kesehatan dan memperdalam kesenjangan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus lebih menaruh perhatian pada UHC yang harus dicapai dengan keuangan yang bijaksana. Aljunid menutup dengan pernyataan bahwa pendekatan strategis dan inisiatif inovatif harus diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.
 Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan Indonesia melanjutkan sesi dengan materi bertajuk “Aligning UHC with Preventive and Primary Care in Indonesia’s National Health Insurance” sebagai bentuk penyelarasan UHC dengan perawatan preventif dan primer dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Di Indonesia, paradigma yang selama ini dianut adalah bahwa masyarakat miskin tidak boleh sakit, namun sejak adanya BPJS Kesehatan, masyarakat miskin tidak perlu membayar jika sakit dan berobat. Itulah fungsi utama BPJS yang dicanangkan sejak 2004. Secara rinci, BPJS memiliki 3 fungsi, yaitu: Strategic Purchasing, Revenue Collection, dan Risk Pooling. BPJS Kesehatan sedang mengupayakan transformasi mutu dengan tiga indikator: lebih mudah, lebih cepat, dan non diskriminasi. Pemanfaatan BPJS meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir yakni sekitar 1,6 milyar rupiah. Dengan selisih yang sangat besar tersebut, BPJS berupaya untuk menggalakkan pelayanan yang lebih preventif dan promotif terhadap masyarakat, khususnya untuk deteksi dini penyakit diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan kanker. BPJS juga mengembangkan Mobile JKN dengan fitur baru bernama BUGAR untuk membantu penyediaan layanan kesehatan digital bagi seluruh masyarakat. Ada pula beberapa inovasi yang digagas BPJS untuk semakin membantu pencapaian UHC di Indonesia. Pada 2024, BPJS Kesehatan berhasil meraih ISSA Good Practice Award.
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan Indonesia melanjutkan sesi dengan materi bertajuk “Aligning UHC with Preventive and Primary Care in Indonesia’s National Health Insurance” sebagai bentuk penyelarasan UHC dengan perawatan preventif dan primer dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Di Indonesia, paradigma yang selama ini dianut adalah bahwa masyarakat miskin tidak boleh sakit, namun sejak adanya BPJS Kesehatan, masyarakat miskin tidak perlu membayar jika sakit dan berobat. Itulah fungsi utama BPJS yang dicanangkan sejak 2004. Secara rinci, BPJS memiliki 3 fungsi, yaitu: Strategic Purchasing, Revenue Collection, dan Risk Pooling. BPJS Kesehatan sedang mengupayakan transformasi mutu dengan tiga indikator: lebih mudah, lebih cepat, dan non diskriminasi. Pemanfaatan BPJS meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir yakni sekitar 1,6 milyar rupiah. Dengan selisih yang sangat besar tersebut, BPJS berupaya untuk menggalakkan pelayanan yang lebih preventif dan promotif terhadap masyarakat, khususnya untuk deteksi dini penyakit diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan kanker. BPJS juga mengembangkan Mobile JKN dengan fitur baru bernama BUGAR untuk membantu penyediaan layanan kesehatan digital bagi seluruh masyarakat. Ada pula beberapa inovasi yang digagas BPJS untuk semakin membantu pencapaian UHC di Indonesia. Pada 2024, BPJS Kesehatan berhasil meraih ISSA Good Practice Award.
 Sesi keempat dibawakan oleh Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., PhD selaku Staf Khusus Keuangan Kesehatan. Prastuti membawakan topik “Strategic Health Financing for System Sustainability in an Era of Global Realignment” terkait strategi pembiayaan kesehatan untuk sistem yang berkesinambungan di era penyelarasan global. Pengeluaran sektor kesehatan Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, dengan hanya 2,7 per PDB pada 2024. Dengan adanya beberapa masalah kesehatan yang muncul di Indonesia, pembiayaan kesehatan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam masa jabatannya. Pembiayaan kesehatan telah dimasukkan ke dalam ketahanan transformasi sistem kesehatan yang baru saja diperkenalkan sebagai pilar keempat. Pemerintah Indonesia bekerja dengan pembiayaan inovatif untuk sistem kesehatan yang berkelanjutan, seperti mobilisasi sumber daya non-tradisional, berorientasi pada hasil, model pembagian risiko, keberlanjutan dan efisiensi, serta fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Pembiayaan inovatif ini digunakan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan kesehatan, meningkatkan keberlanjutan, mendorong efisiensi dan akuntabilitas, mendukung UHC, dan mengatasi tantangan lainnya. Prastuti menyampaikan bahwa terdapat agenda yang berkolaborasi dengan World Bank dan membentuk 3 tingkat sumber daya PFM.
Sesi keempat dibawakan oleh Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., PhD selaku Staf Khusus Keuangan Kesehatan. Prastuti membawakan topik “Strategic Health Financing for System Sustainability in an Era of Global Realignment” terkait strategi pembiayaan kesehatan untuk sistem yang berkesinambungan di era penyelarasan global. Pengeluaran sektor kesehatan Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, dengan hanya 2,7 per PDB pada 2024. Dengan adanya beberapa masalah kesehatan yang muncul di Indonesia, pembiayaan kesehatan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam masa jabatannya. Pembiayaan kesehatan telah dimasukkan ke dalam ketahanan transformasi sistem kesehatan yang baru saja diperkenalkan sebagai pilar keempat. Pemerintah Indonesia bekerja dengan pembiayaan inovatif untuk sistem kesehatan yang berkelanjutan, seperti mobilisasi sumber daya non-tradisional, berorientasi pada hasil, model pembagian risiko, keberlanjutan dan efisiensi, serta fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Pembiayaan inovatif ini digunakan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan kesehatan, meningkatkan keberlanjutan, mendorong efisiensi dan akuntabilitas, mendukung UHC, dan mengatasi tantangan lainnya. Prastuti menyampaikan bahwa terdapat agenda yang berkolaborasi dengan World Bank dan membentuk 3 tingkat sumber daya PFM.
 Pembicara terakhir, Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B.Subsp.onk. (K) selaku Direktur Utama RS Akademik UGM, menyampaikan materi tentang Upaya Green Hospital di Indonesia. Darwito menyampaikan RSA UGM berupaya mengimplementasikan beberapa hasil penelitian lingkungan. Pertama, pemanfaatan air untuk kebutuhan industri (pelayanan kesehatan). Inisiatif ini menggunakan sistem GAMA Rain, program vokasional di UGM. Rumah sakit memanfaatkan kolam resapan untuk pengolahan air limbah dan air perkolasi untuk menyiram tanaman di sekitar rumah sakit. Kedua, rumah sakit memanfaatkan pembangkit listrik mikrohidro dari tekanan air untuk penerangan taman dan panel surya untuk sumber energi rumah sakit. Ketiga, rumah sakit memiliki sistem pengelolaan limbah organik dengan biokonversi maggot. Hasilnya adalah kompos organik untuk pupuk di kebun rumah sakit. Keempat, rumah sakit menggunakan kolaborasi dan integrasi untuk pengembangan kewirausahaan gizi dengan akademisi, industri, dan masyarakat.
Pembicara terakhir, Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B.Subsp.onk. (K) selaku Direktur Utama RS Akademik UGM, menyampaikan materi tentang Upaya Green Hospital di Indonesia. Darwito menyampaikan RSA UGM berupaya mengimplementasikan beberapa hasil penelitian lingkungan. Pertama, pemanfaatan air untuk kebutuhan industri (pelayanan kesehatan). Inisiatif ini menggunakan sistem GAMA Rain, program vokasional di UGM. Rumah sakit memanfaatkan kolam resapan untuk pengolahan air limbah dan air perkolasi untuk menyiram tanaman di sekitar rumah sakit. Kedua, rumah sakit memanfaatkan pembangkit listrik mikrohidro dari tekanan air untuk penerangan taman dan panel surya untuk sumber energi rumah sakit. Ketiga, rumah sakit memiliki sistem pengelolaan limbah organik dengan biokonversi maggot. Hasilnya adalah kompos organik untuk pupuk di kebun rumah sakit. Keempat, rumah sakit menggunakan kolaborasi dan integrasi untuk pengembangan kewirausahaan gizi dengan akademisi, industri, dan masyarakat.
Setelah sesi materi, beberapa tamu undangan dan narasumber memberikan tanggapan untuk materi yang telah disampaikan. Prof Laksono menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber pendanaan untuk sistem pelayanan kesehatannya, begitu pula dengan negara lain, seperti BPJS Kesehatan. Pembicara sebelumnya, Prastuti, telah menyampaikan pentingnya mencari sumber pendanaan lain untuk mendanai sistem pelayanan kesehatan.Jika dibandingkan 30 tahun yang lalu, situasi dunia kini lebih rumit dan isu kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim meningkatkan potensi perkembangan penyakit yang lebih membutuhkan pendanaan. Pendanaan sistem kesehatan yang inovatif menjadi kunci untuk mencapai UHC.
Prof. Supasit Pannarunothai juga menambahkan bahwa kini merupakan saat bagi para generasi muda untuk memaksimalkan potensi penelitian dan menemukan mekanisme pendanaan baru untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di dunia. Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid menggarisbawahi pentingnya melakukan pemetaan sumber-sumber pendanaan dan peruntukannya dengan berbagai institusi yang terlibat. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK menanggapi bahwa BPJS Kesehatan telah membagi tugas dengan Kementerian Kesehatan dan institusi terkait lainnya untuk mendefinisikan hal ini.
Sesi ditutup dengan salah satu peserta yang membagikan hasil rangkumannya atas sesi ini dan pemberian kenang-kenangan kepada seluruh narasumber dan moderator.
Reporter:
Sensa Gudya Sauma Syahra dan Alif Indiralarasati (PKMK UGM)

 Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D,FRSPH selaku Dekan FK-KMK UGM membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa keberlanjutan sistem kesehatan di masa mendatang bergantung pada kebijakan dan keputusan, serta aksi yang kita lakukan saat ini. PGF bukan hanya forum akademik melainkan forum untuk mentransformasi pengetahuan menjadi aksi dan aksi menjadi upaya keberlanjutan guna memperkuat sistem kesehatan dalam rangka transformasi kesehatan. Sistem kesehatan di seluruh dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, tantangan demografi, kegawatdaruratan, dan pandemi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan solusi yang tidak hanya berupa solusi ilmiah, melainkan juga political will, leadership, strategic financing, resiliensi sistem dan adaptability.
Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D,FRSPH selaku Dekan FK-KMK UGM membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa keberlanjutan sistem kesehatan di masa mendatang bergantung pada kebijakan dan keputusan, serta aksi yang kita lakukan saat ini. PGF bukan hanya forum akademik melainkan forum untuk mentransformasi pengetahuan menjadi aksi dan aksi menjadi upaya keberlanjutan guna memperkuat sistem kesehatan dalam rangka transformasi kesehatan. Sistem kesehatan di seluruh dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, tantangan demografi, kegawatdaruratan, dan pandemi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan solusi yang tidak hanya berupa solusi ilmiah, melainkan juga political will, leadership, strategic financing, resiliensi sistem dan adaptability. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI). Prof. Dante menegaskan bahwa pembangunan sistem kesehatan Indonesia kini berfokus pada upaya preventif, sebagaimana tercermin dalam slogan “sedia payung sebelum hujan”. Harapannya sistem kesehatan yang dibangun saat ini mampu melindungi masyarakat di masa mendatang. Perubahan iklim saat ini memberikan dampak besar terhadap sektor kesehatan. Prof. Dante menilai solusi bagi permasalahan sektor kesehatan tidak terbatas pada kesehatan saja, melainkan multi sektoral. Integrasi isu kesehatan ke dalam kebijakan lintas sektor seperti pertanian, infrastruktur, dan pendidikan menjadi sangat penting, terlebih dengan kolaborasi lintas negara. Di saat yang sama, penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan juga terus dilakukan, seperti penguatan laboratorium kesehatan masyarakat dan pemberdayaan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer. Program cek kesehatan gratis yang dimulai tahun ini juga merupakan upaya preventif untuk menurunkan kasus kegawatdaruratan. Selain pencegahan, percepatan respons terhadap dampak perubahan iklim juga menjadi prioritas dengan didukung tenaga kesehatan cadangan dan peningkatan koordinasi lintas pemerintahan. Sementara itu, transformasi kesehatan yang telah dimulai pemerintah sejak 2022 merupakan pondasi dalam membangun ketahanan sistem. Prof. Dante menutup dengan mengajak semua pihak agar mengambil bagian dari upaya preventif saat ini demi melindungi kelompok rentan, menjaga keberlanjutan generasi mendatang, dan membangun sistem yang tangguh menghadapi tantangan masa mendatang.
dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI). Prof. Dante menegaskan bahwa pembangunan sistem kesehatan Indonesia kini berfokus pada upaya preventif, sebagaimana tercermin dalam slogan “sedia payung sebelum hujan”. Harapannya sistem kesehatan yang dibangun saat ini mampu melindungi masyarakat di masa mendatang. Perubahan iklim saat ini memberikan dampak besar terhadap sektor kesehatan. Prof. Dante menilai solusi bagi permasalahan sektor kesehatan tidak terbatas pada kesehatan saja, melainkan multi sektoral. Integrasi isu kesehatan ke dalam kebijakan lintas sektor seperti pertanian, infrastruktur, dan pendidikan menjadi sangat penting, terlebih dengan kolaborasi lintas negara. Di saat yang sama, penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan juga terus dilakukan, seperti penguatan laboratorium kesehatan masyarakat dan pemberdayaan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer. Program cek kesehatan gratis yang dimulai tahun ini juga merupakan upaya preventif untuk menurunkan kasus kegawatdaruratan. Selain pencegahan, percepatan respons terhadap dampak perubahan iklim juga menjadi prioritas dengan didukung tenaga kesehatan cadangan dan peningkatan koordinasi lintas pemerintahan. Sementara itu, transformasi kesehatan yang telah dimulai pemerintah sejak 2022 merupakan pondasi dalam membangun ketahanan sistem. Prof. Dante menutup dengan mengajak semua pihak agar mengambil bagian dari upaya preventif saat ini demi melindungi kelompok rentan, menjaga keberlanjutan generasi mendatang, dan membangun sistem yang tangguh menghadapi tantangan masa mendatang.










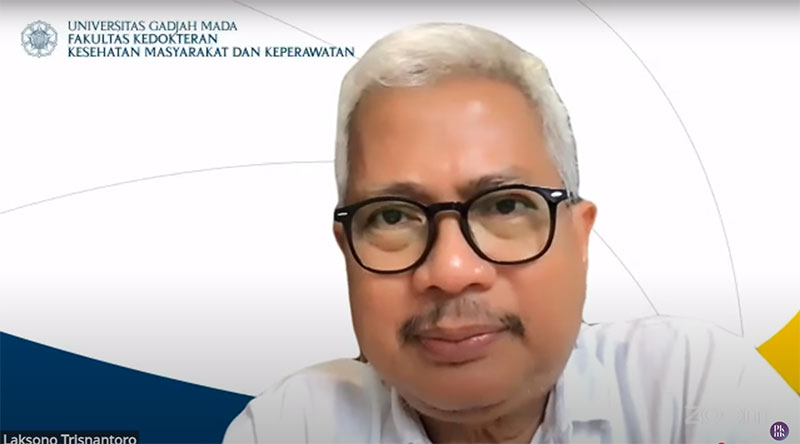

 Barkah memandu para peserta dalam menyusun data anggaran terkait bahan medis habis pakai (BMHP). Peserta menerima materi sebagai bekal untuk simulasi pengumpulan data yang juga meliputi penjelasan detail mengenai tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kelengkapan dan ketersediaan data rumah sakit sangat menentukan keakuratan hasil serta efisiensi proses pengumpulan data.
Barkah memandu para peserta dalam menyusun data anggaran terkait bahan medis habis pakai (BMHP). Peserta menerima materi sebagai bekal untuk simulasi pengumpulan data yang juga meliputi penjelasan detail mengenai tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kelengkapan dan ketersediaan data rumah sakit sangat menentukan keakuratan hasil serta efisiensi proses pengumpulan data. Hari ketiga, Husniawan Prasetyo, SE. memandu simulasi terkait penyusunan tarif berdasarkan unit cost serta pemanfaatannya sebagai alat untuk efisiensi biaya. Husniawan menjelaskan bahwa setelah unit cost berhasil dihitung, data tersebut dapat menjadi acuan penting bagi manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, unit cost tidak hanya digunakan sebagai dasar penentuan tarif, tetapi juga dibandingkan dengan tarif INA-CBG’s berdasarkan hasil perhitungan roll-up unit cost. Dengan demikian, rumah sakit dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif yang berlaku maupun biaya layanan bagi pasien JKN.
Hari ketiga, Husniawan Prasetyo, SE. memandu simulasi terkait penyusunan tarif berdasarkan unit cost serta pemanfaatannya sebagai alat untuk efisiensi biaya. Husniawan menjelaskan bahwa setelah unit cost berhasil dihitung, data tersebut dapat menjadi acuan penting bagi manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, unit cost tidak hanya digunakan sebagai dasar penentuan tarif, tetapi juga dibandingkan dengan tarif INA-CBG’s berdasarkan hasil perhitungan roll-up unit cost. Dengan demikian, rumah sakit dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif yang berlaku maupun biaya layanan bagi pasien JKN.