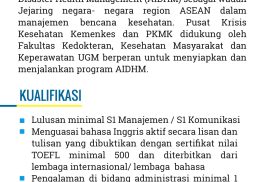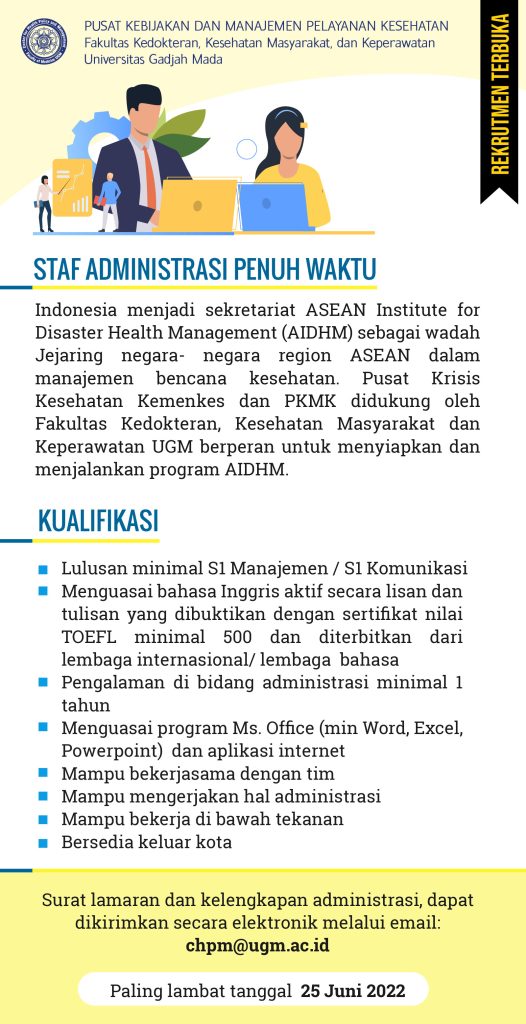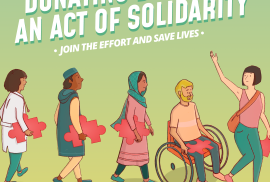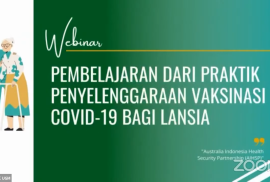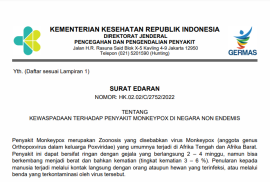Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) baru saja merilis publikasi WHO Quality Toolkit, yang menyediakan alat praktis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Materi ini dikumpulkan bersama untuk pertama kalinya dari berbagai program di WHO. Publikasi ini diharapkan dapat peningkatan kualitas layanan kesehatan di setiap tingkat sistem kesehatan, dari tingkat nasional, daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan di tingkat masyarakat.
Toolkit ini melengkapi publikasi sebelumnya yaitu Quality health services: a planning guide yang menyediakan peta jalan dalam mengambil tindakan di seluruh sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Materi toolkit memberikan langkah-langkah pendekatan praktis yang dapat mendukung implementasi tindakan yang diperlukan. Toolkit ini akan terus diperbarui secara berkala untuk memasukkan informasi dan praktik baik dari WHO.