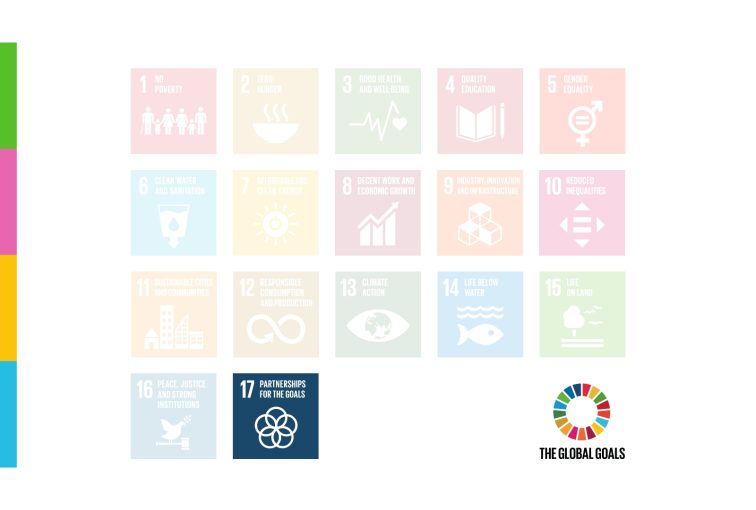
“Perkembangan Kebijakan Komponen-Komponen Sistem Kesehatan di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Pasca COVID-19, 1999-2023”
PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Departemen Sejarah FIB UGM menyelenggarakan Webinar Seri Sejarah Kebijakan Kesehatan “Perkembangan Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Pasca COVID-19, 1999-2023” pada Agustus hingga November 2025. Kali ini webinar mengangkat tema “Pelayanan Kesehatan” yang diselenggarakan pada Selasa (11/11/2025). Webinar ini menyoroti berbagai dinamika dan kebijakan dalam pelayanan kesehatan Indonesia sejak era reformasi hingga masa pasca-pandemi COVID-19. Melalui paparan para pembicara, kegiatan ini mengulas bagaimana desentralisasi, jaminan kesehatan nasional, dan transformasi sistem kesehatan berperan dalam membentuk arah pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan sosial.
 Dalam pengantar seri ini, Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., dalam pengantarnya, Prof. Laksono menekankan pentingnya meninjau perjalanan historis kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia sejak era desentralisasi awal 2000-an hingga reformasi kebijakan terkini. Pihaknya menjelaskan bahwa desentralisasi membawa perubahan besar terhadap peran dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menciptakan dinamika baru dalam tata kelola sektor ini. Prof. Laksono mengajak peserta untuk melihat proses historis transformasi tersebut sebagai catatan penting bagi pengembangan kebijakan masa depan. Prof Laksono menegaskan pentingnya dokumentasi dan kajian sejarah seperti webinar ini sebagai sumber pembelajaran publik. Mengutip sejarawan Stephen Ambrose, “melihat masa lalu adalah sumber pengetahuan, dan masa depan adalah sumber harapan,” menandakan bahwa studi sejarah kebijakan kesehatan bersifat reflektif dan prospektif. Sebagai penutup, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, Iztihadun Nisa, SKM., MPH., dan Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil yang mewakili kolaborasi lintas disiplin antara Departemen Sejarah FIB dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, dalam upaya menelusuri dan menuliskan sejarah kebijakan kesehatan Indonesia.
Dalam pengantar seri ini, Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., dalam pengantarnya, Prof. Laksono menekankan pentingnya meninjau perjalanan historis kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia sejak era desentralisasi awal 2000-an hingga reformasi kebijakan terkini. Pihaknya menjelaskan bahwa desentralisasi membawa perubahan besar terhadap peran dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menciptakan dinamika baru dalam tata kelola sektor ini. Prof. Laksono mengajak peserta untuk melihat proses historis transformasi tersebut sebagai catatan penting bagi pengembangan kebijakan masa depan. Prof Laksono menegaskan pentingnya dokumentasi dan kajian sejarah seperti webinar ini sebagai sumber pembelajaran publik. Mengutip sejarawan Stephen Ambrose, “melihat masa lalu adalah sumber pengetahuan, dan masa depan adalah sumber harapan,” menandakan bahwa studi sejarah kebijakan kesehatan bersifat reflektif dan prospektif. Sebagai penutup, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, Iztihadun Nisa, SKM., MPH., dan Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil yang mewakili kolaborasi lintas disiplin antara Departemen Sejarah FIB dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, dalam upaya menelusuri dan menuliskan sejarah kebijakan kesehatan Indonesia.
 Dalam paparannya, Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. menjelaskan perjalanan kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia selama dua dekade, dari masa desentralisasi (1999–2009) hingga lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN, 2009–2019). Pemaparannya merujuk pada hasil penelitian lintas disiplin yang terangkum dalam buku Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Dari Desentralisasi hingga Pasca COVID-19, kolaborasi antara FKKMK dan FIB UGM dengan dukungan Kementerian Kesehatan RI. Dr. Wahid menegaskan bahwa kebijakan kesehatan perlu dipahami secara luas, mencakup keputusan publik dan swasta yang mempengaruhi sistem kesehatan nasional. Dr Wahid menggunakan kerangka six building blocks WHO seperti pelayanan, tenaga, informasi, teknologi dan produk, pembiayaan, serta tata kelola sebagai dasar analisis keterpaduan sistem kesehatan. Pada periode pertama (1999–2009), desentralisasi menjadi titik balik penting dalam tata kelola kesehatan. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada daerah untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperluas layanan. Namun, penelitian menunjukkan banyak daerah belum siap, sehingga muncul ketimpangan antar wilayah, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meski demikian, lahir sejumlah kebijakan kunci seperti Gerakan Nasional Kehamilan Aman, Program perbaikan gizi dan pencegahan stunting, Pekan Imunisasi Nasional, serta Paradigma Sehat dan Visi Indonesia Sehat 2010. Pembentukan BNPB (2008) juga menjadi tonggak kesiapsiagaan bencana di sektor kesehatan.
Dalam paparannya, Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. menjelaskan perjalanan kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia selama dua dekade, dari masa desentralisasi (1999–2009) hingga lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN, 2009–2019). Pemaparannya merujuk pada hasil penelitian lintas disiplin yang terangkum dalam buku Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Dari Desentralisasi hingga Pasca COVID-19, kolaborasi antara FKKMK dan FIB UGM dengan dukungan Kementerian Kesehatan RI. Dr. Wahid menegaskan bahwa kebijakan kesehatan perlu dipahami secara luas, mencakup keputusan publik dan swasta yang mempengaruhi sistem kesehatan nasional. Dr Wahid menggunakan kerangka six building blocks WHO seperti pelayanan, tenaga, informasi, teknologi dan produk, pembiayaan, serta tata kelola sebagai dasar analisis keterpaduan sistem kesehatan. Pada periode pertama (1999–2009), desentralisasi menjadi titik balik penting dalam tata kelola kesehatan. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada daerah untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperluas layanan. Namun, penelitian menunjukkan banyak daerah belum siap, sehingga muncul ketimpangan antar wilayah, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meski demikian, lahir sejumlah kebijakan kunci seperti Gerakan Nasional Kehamilan Aman, Program perbaikan gizi dan pencegahan stunting, Pekan Imunisasi Nasional, serta Paradigma Sehat dan Visi Indonesia Sehat 2010. Pembentukan BNPB (2008) juga menjadi tonggak kesiapsiagaan bencana di sektor kesehatan.
Memasuki periode kedua (2009–2019), arah kebijakan bergeser pada penguatan sistem JKN dan perluasan akses layanan. Pemerintah mendorong kolaborasi fasilitas kesehatan dengan BPJS, membuka investasi swasta, serta memperkuat mutu dan keselamatan pasien melalui standar internasional seperti JCI. Layanan primer dan berbasis keluarga diperluas melalui Program Indonesia Sehat, disertai perhatian pada layanan paliatif, kesehatan jiwa (Program Indonesia Bebas Pasung 2012), serta pengembangan pengobatan tradisional dan wisata kesehatan. Kendati berbagai reformasi dilakukan, Dr. Wahid menilai sistem kesehatan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural: ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, dan kesiapan kelembagaan rumah sakit yang belum merata dimana kondisi yang kian tampak saat pandemi COVID-19. Beliau menutup dengan refleksi bahwa dua dekade reformasi kesehatan menunjukkan kemajuan penting, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan dasar tata kelola dan pemerataan layanan. Karena itu, memahami dinamika 1999–2019 menjadi pijakan penting bagi transformasi kebijakan kesehatan yang lebih berkelanjutan ke depan.
 Paparan berikutnya dilanjutkan oleh Iztihadun Nisa, SKM., MPH. yang membahas fase penting dalam sejarah kebijakan kesehatan Indonesia, yaitu masa pandemi COVID-19 dan transformasi sistem kesehatan pasca-pandemi. beliau menjelaskan bagaimana krisis global tersebut menjadi momentum penting untuk mereformasi tata kelola pelayanan kesehatan nasional secara menyeluruh. Sebagai dasar analisis, Atun menegaskan bahwa penulisan sejarah kebijakan ini berangkat dari amandemen UUD 1945 serta berbagai peraturan kesehatan di tingkat pusat dan daerah. beliau mengingatkan bahwa pandemi bukan peristiwa baru dalam sejarah, melainkan pola berulang yang pernah terjadi seperti pada wabah flu burung. Dari perspektif sejarah, pandemi menjadi cermin rapuhnya sistem kesehatan sekaligus pemicu perubahan struktural yang besar.
Paparan berikutnya dilanjutkan oleh Iztihadun Nisa, SKM., MPH. yang membahas fase penting dalam sejarah kebijakan kesehatan Indonesia, yaitu masa pandemi COVID-19 dan transformasi sistem kesehatan pasca-pandemi. beliau menjelaskan bagaimana krisis global tersebut menjadi momentum penting untuk mereformasi tata kelola pelayanan kesehatan nasional secara menyeluruh. Sebagai dasar analisis, Atun menegaskan bahwa penulisan sejarah kebijakan ini berangkat dari amandemen UUD 1945 serta berbagai peraturan kesehatan di tingkat pusat dan daerah. beliau mengingatkan bahwa pandemi bukan peristiwa baru dalam sejarah, melainkan pola berulang yang pernah terjadi seperti pada wabah flu burung. Dari perspektif sejarah, pandemi menjadi cermin rapuhnya sistem kesehatan sekaligus pemicu perubahan struktural yang besar.
Dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Kebijakan ini disertai pembentukan Gugus Tugas COVID-19, yang melibatkan lintas sektor, bukan hanya bidang kesehatan, melainkan juga keamanan, pemerintahan, dan sosial yang menjadi model awal kolaborasi multisektor yang kuat. Masa pandemi menunjukkan kerentanan sarana dan prasarana kesehatan nasional, ditandai keterbatasan alat, ruang isolasi, dan sumber daya manusia. Pemerintah kemudian menerapkan strategi adaptif melalui kebijakan “3T” (Testing, Tracing, Treatment) berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Keputusan Menkes Nomor 107 Tahun 2020. Program ini dijalankan secara kolaboratif oleh berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Memasuki fase transformasi sistem kesehatan pasca-pandemi, Kementerian Kesehatan meluncurkan enam pilar transformasi kesehatan, dengan fokus utama pada pelayanan primer dan rujukan. Pada pilar pertama, transformasi pelayanan primer diarahkan untuk memperkuat screening kesehatan di tingkat masyarakat melalui modernisasi alat di Puskesmas dan Posyandu, revitalisasi fasilitas, digitalisasi pencatatan, serta perluasan imunisasi (termasuk vaksin HPV, PCV, dan Rotavirus). Program ini sejalan dengan visi “Life long and life well,” yang menekankan peningkatan kesehatan fisik dan mental sepanjang siklus hidup. Pada pilar kedua, transformasi layanan rujukan dilakukan dengan membagi rumah sakit ke dalam tiga tingkat (madya, utama, dan paripurna), memperluas fasilitas seperti MRI, CAT Lab, dan PET Scan, serta meningkatkan layanan untuk penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, dan urologi. Pemerintah juga menegakkan standar mutu ruang rawat inap nasional (Perpres Nomor 59 Tahun 2024) dan memperkuat kolaborasi internasional rumah sakit. Kebijakan Hospital-Based Education diatur untuk menjadikan rumah sakit pendidikan sebagai pusat utama pelatihan tenaga medis, sementara UU Nomor 17 Tahun 2023 memberi dasar hukum baru bagi transplantasi organ dan kolaborasi rumah sakit pemerintah-swasta. Dalam era pasca-pandemi, kebijakan diperkuat melalui UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 (Omnibus Law Kesehatan). Fokus utamanya meliputi: integrasi layanan primer berbasis siklus hidup, penguatan medical wellness dan kesehatan paliatif, serta penegakan mutu dan akreditasi. Layanan pengobatan tradisional juga dilembagakan dengan pengawasan ketat untuk menjamin keamanan dan manfaatnya.
Sebagai penutup, Atun menegaskan bahwa pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang mengungkap lemahnya fondasi dan koordinasi sistem kesehatan nasional. Dari krisis tersebut, Kementerian Kesehatan mengambil langkah besar melalui Transformasi Kesehatan 6 Pilar, sebagai bentuk perbaikan menyeluruh pasca stagnasi panjang sejak era desentralisasi. Menurutnya, terbitnya UU Kesehatan 2023 menandai era baru dalam reformasi sistem kesehatan Indonesia, dengan tujuan mengharmonisasi regulasi dan memperkuat peran pemerintah sebagai regulator utama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.
Informasi selengkapnya:
https://sejarahkesehatan.net/seri-webinar-tematik-sejarah-kebijakan-kesehatan/
Rekaman kegiatan:
https://www.youtube.com/live/Fkq0d_zj9WU?si=9pdsV8LlwrZTzsOp
Reporter:
Galen Sousan Amory, S. Sej.
SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera,
SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
